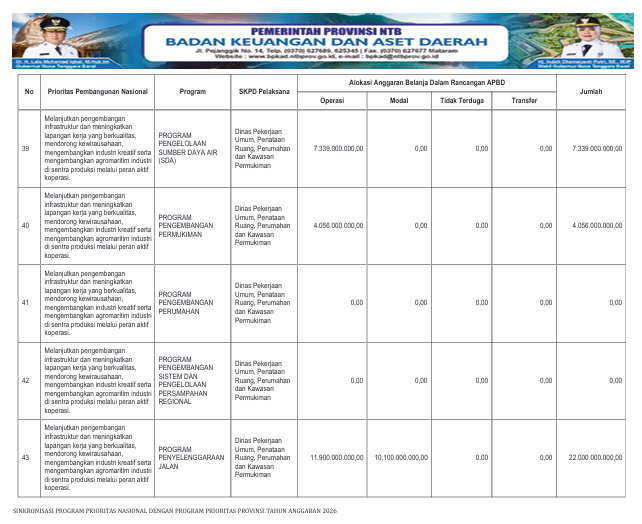Oleh : N Laely
Langit masih sembab usai menghamburkan begitu banyak air, ketika pagi itu dapur pecah oleh keramik beradu lantai marmer. Selusin piring keramik dengan bunga tulip kuning di pusatnya berubah menjadi mozaik yang terserak bertindihan. Potongan puzzle yang terhambur. Ibu menangis tak bersuara di atas keping piring-piring itu. Piring-piring yang dipakai hanya pada acara makan istimewa. Alya terpaku, hanya matanya yang bergerak antara piring dan ibu berganti-ganti. Entah mengapa, inginnya menikmati pelukan ibu menguap seketika. Peluk yang selalu bisa menenangkannya.
Alya masih tidak beranjak ketika Ayah dengan mata setengah tertutup, mengantuk, tiba di dapur menyaksikan lantai yang dipenuhi beling. Hanya butuh satu detik sampai laki-laki itu menghambur ke arah ibu, mendorong kursi rodanya keluar dari dapur dan melihat ke arah Alya sekilas. Alya masih membeku bahkan ketika Don, adiknya akhirnya tiba juga di tempat itu. Setelah Don berlutut memunguti pecahan itu barulah ia tersadar.
Alya gontai meninggalkan dapur, menyeberangi ruang tengah, melewati begitu saja Ayah yang mendekap Ibu, menenangkannya. Alya berpikir itu terlalu berlebihan. Dia yang seharusnya butuh ditenangkan. Ia yang baru saja kehilangan suami ini, dipecat perusahaan tempatnya bekerja selama tujuh tahun. Dua kehilangan yang tak tertanggung ketika datang di waktu nyaris bersamaan.
Suaminya yang merantau ke Jiran itu sudah tak pulang lima tahun. Berhemat, dalihnya. Juga cari aman agar tak kena tangkap saat razia. Visanya cuma melancong, tak boleh bekerja. Target awalnya hanya dua tahun. Tiga paling lama. Tapi tanggung, bossnya sudah jatuh percaya padanya. Dua tahun lagi. Alya setuju. Tiga tahun tak lama, ditambah dua tahun lagi tak akan ada bedanya.
Tapi dua minggu lalu laki-laki itu pulang. Satu bulan lebih cepat dari janjinya. Ia pulang tinggal KTP dan paspor. Tubuhnya, tulang, daging dan kulit habis jadi abu. Ia terbakar bersama terbakarnya gudang majikannya. Janjinya tak bisa genap. Tak ada yang bisa genap.
Ibu membenci laki-laki itu karena membawa pergi Alya ketika mimpi melihat putrinya berdiri di pintu pesawat dengan seragam elegan dan senyum menawan hampir terwujud. Alya dibawa pergi tanpa janji apapun, kepastian apa saja. Tak ada ibu yang tak meradang. Bahkan setelah setahun usia pernikahan Alya, Ibu masih menyimpan bara kecewa yang begitu gampang terpantik apa saja menjelma amarah. Tapi Alya tak menepi, dihadapinya badai amarah itu dengan lapang. Tak pernah surut ia ke pantai, sampai lengkung lengan Ibu mendekapnya erat seperti dulu. Tiga belas bulan, Ibu akhirnya memeluknya dengan mata penuh air. Alya tak henti mengucap sukur. Mereka berbaikan. Lautan kembali tenang.
Tapi pagi ini ibu melepas begitu saja piring kesayangannya meluncur menemui lantai ketika melihat Alya. Alya belum berkata apa juga. Ia tiba semalam setelah menempuh perjalanan empat jam, meniti ombak lautan dengan ferry hanya untuk menemui ibu, mencari peluknya. Alya bahkan tak bisa menunggu pesawat, bandara ditutup karena abu gunung. Walau tenang air bagi Alya selalu melelahkan. Tapi ia benar-benar tak bisa menunggu, harus segera bertemu ibu.
Ibu selalu tahu ketika Alya membutuhkannya. Ibu seringkali tiba-tiba sudah berdiri di pintu kostnya saat kuliah, atau di depan rumah kontrakan ketika Alya telah menikah. Ibu adalah selalu malaikatnya. Hanya sejak dua tahun lalu langkah ibu terbatas. Kursi roda dan tempat tidur memakunya bergantian. Setengah tubuhnya mati. Sejak itu ibu hanya bisa menelponnya.
Alya sering berbohong di telpon. Ia selalu baik saja. Ia tak mau memberatkan lagi pikiran ibu. Kelumpuhan saja sudah begitu menyakitkan, tak perlu lagi menambahnya dengan keluh kontrakan yang belum terbayar, boss yang merayunya berkhianat, melecehkannya, hari-hari kesepian yang panjang…
Ibu sudah tidur ketika ia tiba. Seisi rumah begitu. Alya sempat melihat ibu di kamarnya, tidur dengan wajah muram dan dahi berkerut. Begitu lelah dan berat. Alya menciumnya. Ibu tidak terbangun tapi tersenyum. Kerut di dahinya meregang, wajah muramnya tenang. Ibu tahu Alya di situ. Alya sedikit lega. Ia lalu pergi ke kamarnya, bekas kamarnya yang selalu dibersihkan, berjaga seolah ia akan pulang setiap saat.
“Kau bisa pulang kapan saja,” bisik Ibu ketika Alya pamit mengikuti suaminya tinggal di Bali.
Alya mengangguk, “Alya akan selalu pulang ke Ibu,” itu sudah pasti. Hatinya tidak bisa mencari rumah lain. Tak akan terganti bahkan oleh suaminya. Sejauh apapun ia pergi.
Tapi pagi ini ibu begitu terkejut melihatnya. Seolah tak berharap menemuinya. Alya bahkan belum berkata suara. Wajahnya juga dibuat berbahagia. Alya sudah melatihnya. Senyum hingga kedip mata, Alya harus menutupi gunung yang sesak menghimpitnya, sedih dan susahnya. Marah dan kecewanya.
Apakah ibu membacanya hanya dengan tatap sekilas itu? Alya pandai memanipulasi pandangan orang, berpura-pura bahagia. Setidaknya itu berhasil untuk semua teman kerjanya. Alya tahu ibu memahaminya lebih dalam, karenanya tak perlu seterkejut itu, bukan? Atau apakah ia terlihat begitu menyedihkan?
Alya mencari cermin di kamar mandi. Cerminnya berkarat ditumpuk pula oleh embun, sisa dingin hujan dini hari tadi. Alya tidak bisa melihat dirinya. Ia keluar, butuh udara segar. Bunga-bunga di halaman depan biasanya bisa menenangkan. Alya tak bisa menemui bunga-bunga. Halaman hanya berisi rumput liar dan rumpun mawar yang kehilangan warna, tanpa bunga. Cabang-cabangnya tumbuh merambat tak jelas arah, menyambar apa saja, menancapkan duri-duri di mana saja.
Ibu tak bisa lagi berkebun, bunga-bunga tumbuh sesukanya, menyemak, mengering. Alya seolah baru tersadar. Tangan ibu yang membawa hidup dan kegembiraan pada tanaman beraneka itu telah begitu jauh tenggelam. Tangan itu tak lagi bisa menghentikan luka, tak lagi bisa mendekap hangat menghalau sendu. Alya seharusnya tak berharap. Alya seharusnya ganti mengulurkan tangan. Bahkan meski tangannya terasa begitu dingin dan berduri.
Alya masuk mencari Ibu. Alya ingin memeluknya. Biarpun dingin, lengannya tentu masih dikenali ibu. Mungkin bisa sedikit menguatkan. Ditemuinya ibu berbaring di kamar, mendekap sesuatu di dada dengan jejak air mulai di pelupuk mata. Alya mendekat ragu. Ayah masuk tepat ketika Alya sampai di sisi ibu. Tergesa dengan wajah mengeras.
“Sudah ditemukan. Don pergi menjemputnya. Mereka akan tiba sebentar lagi.”
Ibu mengangguk, air mengalir lagi dari matanya, deras. Dekapnya yang terisi bingkai foto itu semakin rapat. Ayah mengelus lengan itu lembut.
Alya mengaduh diam-diam. Nyeri di dadanya melihat dua orang tunya seperti itu. Terutama ibu. Mengapa pedih tak meninggalkannya meski waktu sudah mengambil begitu banyak hal. Tidak bisakah pedih melihat hanya sebagian tubuhnya yang masih hidup? Apakah karena jantung dan hatinya masih kuat bertahan memanggul semua beban?
“Aku ingin memeluknya sekali lagi. Satu kali saja. Dia pasti begitu kedinginan.” Ibu mengulurkan tangannya pada Ayah, membiarkan bingkai foto itu bergulir di sisi tubuhnya.
“Tidak ada yang memeluknya, hujan begitu deras kemarin,”
Alya teringat hujan di tengah laut semalam, ketika ia menyeberang. Ia diguyur hujan yang jatuh tiba-tiba itu di geladak. Ia basah kedinginan. Orang-orang tak hirau. Mereka berebut masuk mencari hangat. Alya juga tak hirau akan dirinya. Ia tak merasakan dingin sama sekali. Ia senang melihat laut begitu tenang.
Ayah mengangkat tubuh ibu, memindahkannya ke kursi roda. Bingkai foto itu tersambar sweater ibu, jatuh di kaki Alya. Alya memungutnya, mendapati dirinya bersama ibu usai akad nikah. Mereka berdua tersenyum. Alya tidak ingat foto itu. Tapi senang melihatnya. Dibawanya foto itu menyusul ibu yang didorong Ayah ke ruang tengah.
Sebuah ambulans berhenti tepat di depan rumah. Alya bisa melihatnya dari jendela. Pun ibu dan ayah. Tak lama berselang Don masuk diiringi beberapa orang membawa sebuah kantong jenazah.
“Alya…” ibu menyeru tertahan, pedih dan pahit menyongsong rombongan kecil itu.
Alya tergugu, membeku. Bingkai foto itu terpelanting.
Air begitu deras menghujaninya dari langit dan laut begitu biru jernih. Tenang dan dalam. Alya menggigil kedinginan. Ia berusaha meraih lengan ibu, begitu jauh. Alya letih menjangkaunya. Alya sudah menyerah ketika ibu datang memberikan dua lengannya. Lengan yang nyatanya jauh lebih hangat dari yang bisa diingatnya.(*)