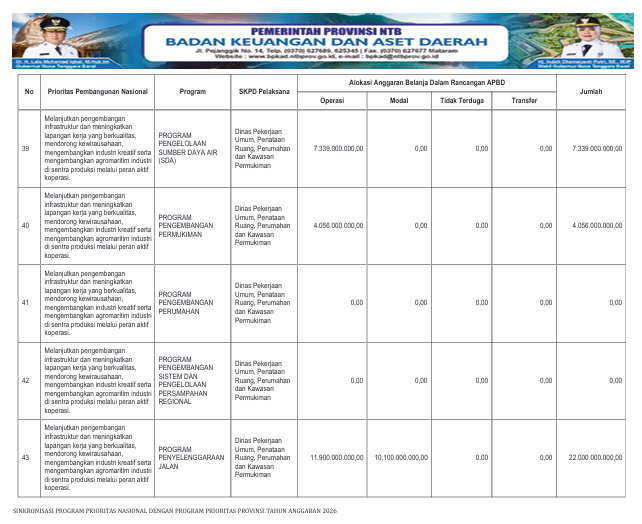Temanku itu mengetuk pintu apartemen sesaat setelah aku mematikan lampu untuk tidur. Hujan awet dan tipis-tipis mengguyur jendela juga barangkali beberapa laksa peristiwa di halaman depan. Malam sudah larut dan enggan mengangkat dingin. “Mirna, buka pintu. Buka pintu ...” Suara itu tergesa.
Aku bangkit, melangkah sambil mengusap-usap sela mata yang sudah memerah entah sebab berjam-jam di depan laptop, entah sebab mengantuk, aku tak tahu, mengantuk dan lelah selalu datang bersamaan, menjadi kutukan kota bagi karyawan kantoran macam diriku. Aku membukakan temanku itu pintu. Dia sangat murung dan basah. Bersama langkahnya, angin dingin yang mengantar lembab juga berteduh ke balik pintu.
“Kamu kenapa?”
Dia masuk, diam. Duduk di bangku kerja dan menunduk. Rambutnya yang sebahu dan basah itu sepertinya tak pernah disisir. “Kau tau, Mir? Semua lelaki barangkali berniat batalkan janji.” Katanya tiba-tiba. Pastilah lelaki yang dia maksud adalah pacarnya yang sudah tiga tahun berhubungan dengannya. Tadi sore dia katakan bahwa pacarnya sangat baik padanya. Aku juga tahu bahwa dua bulan lagi dia akan menikah dengan pacarnya itu. Dan yang aku tahu mereka tidak pernah mengalami masalah serius.
“Ada masalah apa?”
Temanku itu menatapku. Aku bisa melihat, di matanya terdapat keputusasaan yang pernah aku lihat satu tahun lalu ketika kakaknya menghamili seorang wanita kampung. Pastilah yang dilakukan pacarnya itu sangat fatal, hingga sekarang aku melihat mata yang sama seperti pada kejadian kakaknya itu. “Jangan pernah cintai lelaki, Mirna. Tidak ada yang dapat kau percaya dari mereka,” katanya kemudian.
“Ada masalah apa?” Aku mengulang pertanyaanku.
Dia tidak menjawab. Aku yang masih berdiri di ambang pintu, mengambilkannya handuk kimono milikku. “Ceritalah sedikit,” ucapku sambil mengenakan kimono itu di tubuh basahnya tanpa memintanya menanggalkan pakaian terlebih dahulu. Dia menarik tubuhku, lalu menenggelamkan wajahnya di dadaku. Dia menangis sejadinya. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku mengelus rambutnya yang sudah di cat warna, membalas pelukannya dengan pelukanku.
“Dia ...”
Ucapannya terputus. Isaknya semakin dalam dan sedih. “Iya, dia kenapa?” Aku terus mengelus rambutnya.
“Dia baru kemarin berjanji tidak akan meninggalkanku. Dia baru kemarin mengatakan akan terus kuat sampai aku dan dia bersama,”
“Terus kenapa?”
“Dia akan pergi, Mirna. Dia akan pergi.” Air matanya sekarang sudah menembus piyamaku dan membasahi sela dadaku.
“Dia dengan orang lain?” Celetukku.
“Tidak. Tidak seperti itu.”
“Terus, bagaimana?”
Hujan terdengar mereda. Dari dalam, kaca jendela seperti berembun. Temanku itu belum juga mengangkat wajahnya dari dadaku. “Dia kecelakaan.” Katanya lirih. Aku memeluk kepala juga mengecup ubun-ubunnya lama. Aroma hujan menguap dari kepalanya, yang kemudian kuendus dalam-dalam, “Ada aku. Tenanglah.” Ucapku kemudian.
“Dia mungkin meninggal, Mir. Dia bisa saja meninggal. Kamu mengerti?”
Aku diam. Merasakan seluruh kepedihan dalam dirinya, yang kemudian juga ingin aku tanggungkan kedalam diriku. “Satu minggu lalu, aku dan dia memesan desain surat undangan pernikahan, Mir. Satu minggu lalu aku dan dia memilih-milih jas dan gaun yang akan kami kenakan di pernikahan nanti. Satu minggu lalu ...” Belum sempat dia mengusaikan ucapannya, aku memeluk kepalanya lebih keras agar wajahnya lebih dalam tenggelam ke dadaku, “Sudah. Jangan sebut-sebut kenangan itu. Kamu hanya akan semakin sakit. Sekarang, menangis saja sepuasnya, aku akan menemanimu.”
Isaknya menjadi-jadi. Temanku itu terus menangis dengan parah. Aku mengenalnya periang dan ramah. Beberapa tahun lalu, bahkan dia menyapaku terlebih dahulu ketika aku hendak melamar kerja di sebuah perusahaan yang sekarang aku dan dia bekerja di sana. Sebagai rekan kerja, aku dan dia sangat dekat. Dia cantik, sama sepertiku.
Lelaki yang sekarang telah jadi tunangannya itu dikenalnya di tempat kerja kami juga. Lelaki itu juga karyawan biasa. Awalnya temanku itu bertemu dengan lelaki itu di suatu makan siang dengan sebuah kebetulan yang biasa. Lelaki itu membawa nampan makan siangnya, menawarkan diri agar satu meja dengan kami. Kami menyilakan, lalu berkenalan.
Sejak saat itulah temanku itu mulai dekat dengan lelaki itu. Tak aku tahu pasti sejak kapan mereka saling menyukai, lantas berpacaran pada akhirnya. Jelasnya, sejak saat itulah aku dan temanku itu jarang bertemu sebab dia sibuk habiskan waktu dengan lelaki yang telah jadi pacarnya itu.
Sejak saat itu juga, aku kesepian. Sebab di kantor, semua orang –terkecuali temanku itu- bersandiwara, beramah-tamah adalah hal remeh-temeh. Ada yang datang hanya pada saat butuh, pada saat tidak ada keperluan, hilang tak ada. Seusai kerja, aku selalu langsung pulang ke kontrakan, tanpa harus mampir ke taman atau paling tidak duduk di koridor untuk berbicang dan melepas penat dengan temanku itu. Diam-diam aku tak menyukai hubungan mereka, sebab membuatku jauh dengannya, bahkan aku tak pernah lagi menemuinya di apartemennya yang hanya bersekat barbershop dengan apartemenku. Aku tak dapat pura-pura terus merestui jika sepi harus mulai kutanggung sendiri.
Bukan tanpa sebab aku sangat menyayangi temanku itu. Sebelumnya aku pernah memiliki seorang teman sewaktu kuliah, dia baik. Sangat baik. Juga seorang lelaki yang aku sukai, dan tidak pernah sempat aku miliki dikarenakan teman baikku itu justru menikah tiba-tiba dengan lelaki sialan ini. Selain itu, aku juga jauh dari keluarga. Papa adalah seorang manager perusahaan, dan mama selalu sibuk rapat di kantor dewan. Karena merasa jauh, aku memutuskan untuk menolak bekerja di perusahaan papa. Tentu, beberapa kesepian itu membuatku tidak mau kehilangan lagi. Kehilangan temanku itu.
Sampai satu minggu lalu, temanku itu mengatakan bahwa tiga bulan lagi dia akan menikah dengan pacarnya. Aku tersenyum -entah bahagia atau kecewa- waktu itu, mengucapkan selamat dan menanyai kabarnya. Dia jadi sering izin tak masuk kerja dengan alasan mempersiapkan nikahan. Rasa rindu kentara dalam dada, “Bagaimana setelah menikah nanti? Apakah temanku itu akan memiliki waktu buatku?” Paling tidak pertanyaan itu yang paling sering menggangguku sebelum tidur.
***
“Bagaimana ceritanya?” Aku menanyai temanku itu setelah terasa tangisnya mereda.
Dia berusaha untuk sedikit menarik kepalanya agar tidak terlalu tenggelam dalam dadaku, “Dia kecelakaan di jalan.” Ucapnya lirih.
“Bagaimana?”
“Sepulang dari rumah tadi, kau tahu sendiri hujan sangat deras. Barangkali hujan menghalangi pandangannya, sampai entah bagaimana dia kecelakaan di jalan.”
“Kamu tahu dari mana?”
“Rumah sakit menelpon keluarga dan keluarga mengabarkannya padaku.”
“Kenapa tidak langsung ke rumah sakit?”
“Justru itu, aku ke sini untuk mengajakmu ke sana, menemaniku.”
“Tenangkan diri di sini dulu. Denganku,” kataku “... hanya kita, semoga seterusnya tanpa dia.” Lanjutku dalam hati.
“Semoga dia selamat,”
Aku masih memeluk kepalanya, tak mau melepaskan dan dilepaskan. Aku sangat menyayangi dan merindukan temanku itu. “Bagaimana kalau kita ke sana sekarang?” Ucapnya lagi. Aku mempererat pelukanku di kepala temanku itu lagi, menenggelamkannya dalam-dalam di dadaku, juga mengecup ubun-ubunnya lama. Aroma hujan menguap dari kepalanya, yang kemudian kuendus dalam-dalam. Dengan tangan kanan, aku meraih handphone yang tergeletak di meja kerja, menulis sebuah pesan: “Kalian harus pastikan bahwa lelaki itu benar-benar mati."
Lombok Timur, 2020
Eyok El-Abrorii. Lahir di Sakra Barat, Lombok Timur.