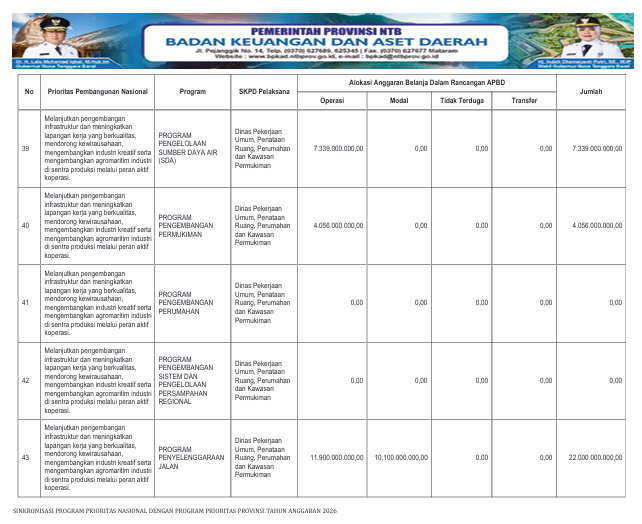Cerpen : Rifat Khan
Tode. Entah mengapa setiap kali mengingat nama itu, tubuhku seperti menggigil. Tode adalah lelaki cerdas dengan badan kurus tinggi. Rambutnya sedikit gondrong, dan giginya, rapi berbaris. Putih. Ya, dulu aku teramat mengagumi, sampai pada teramat mencintainya. Tode dengan sekejap mampu membuat sebuah lubang besar di hatiku, yang masih menganga hingga kini.
Pertemuan kami amat sederhana, diawali dengan segelas teh hangat di kantin kampus. Rambut gondrongnya sesekali diterbangkan angin. Dan itu sungguh menambah pesonanya. Semua orang, menurutku, akan mudah menyukai dan mencintai Tode, meskipun, mungkin jika kau lelaki. Bicaranya luwes, sopan dan tidak membosankan.
"Cinta dan perkawinan adalah dua hal berbeda, Han" Tode memandangku. Saat itu kami tengah membincangkan masalah perkawinan. Sebab di kota ini, adat kadang membuat perkawinan menjadi rumit. Sebagai contoh, keluarga keturunan Baiq dan Lalu, yang menganggap dirinya bangsawan. Mereka akan meminta mahar yang tinggi, apalagi jika perempuan mereka sudah sarjana, dan dilamar oleh pemuda yang bukan sarjana. Kadang maharnya sampai ratusan juta. Belum lagi ditambah beberapa ekor sapi. Kadang juga beberapa petak sawah.
"Maksudmu?" Aku memandang lekat ke matanya. Dua bola mata yang hitam dan terasa begitu teduh. Bulu matanya yang lentik, garis mata dan hidung yang menawan. Aku semakin jatuh cinta pada Tode.
"Saat pacaran, kau bisa memilih dengan siapa saja, tapi ketika memutuskan menikah. Kau musti berpikir ulang. Sebab, kota ini akan selalu begini. Kesenjangan tetap ada. Tak mungkin kau akan terus ngotot menikahi perempuan bangsawan, sedang kau hanya turunan biasa-biasa saja. Tak mungkin kau akan menikahi seorang gadis yang pekerjaannya jauh di atasmu. Sedang kau, mungkin hanya sebatas guru honorer. Kau akan dijajah saat berumah tangga" Tode tersenyum saat mengakhiri kalimatnya. Aku masih memandangnya.
Dalam diam beberapa saat, Tode nyeletuk, "Kalo aku. Mending nikahi gadis yang sudah kecil yatim piatu. Yang sudah biasa susah. Kau tau sendiri kan, kerjaanku hanya nulis, kadang dimuat, kadang gak sama sekali. Penghasilan tak pernah pasti" Tode tertawa. Aku ikut tertawa dan masih larut memandang matanya.
****
Tode. Lelaki Itu ibarat mata air di padang pasir. Pernah aku merasa jenuh, tugas kuliah numpuk, belum lagi tonggakan SPP yang menjadi-jadi. Dia meneleponku, suaranya begitu lembut, "Aku ada sedikit uang, kau mau ikut? Ke Selong. Banyak hal menarik di sana. Lumayanlah buat ongkos bemo dan makan kita seharian, aku yang tanggung"
Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan ajakannya. Tode datang dengan setelan kemeja flanel merah dan jeans sobek di lututnya. Rambutnya basah, seperti baru saja keramas. Aroma shampoo menguak di penciumanku. Wajahnya terlihat cerah, dan aku ikut larut dalam kecerahan itu. "Siap?" Dia menepuk pundakku. Aku mengangguk.
Perjalanan kami hanya satu jam saja untuk sampai di kota itu. Suasana alam yang hijau menyapa kami di sebuah areal yang diberi nama Taman Rinjani. Meski orang-orang belum ramai berkunjung ke Taman itu.
"Di sana, yang tertutup gerbang itu adalah Makam Pahlawan. Pahlawan yang gugur semasa penjajahan" Tode menunjuk ke sebuah areal yang dikelilingi tembok. Areal yang dekat dengan Taman Rinjani. Aroma parfumnya diterbangkan angin, Alexander warna kuning. Aku menatap dagunya yang panjang. Dan bibirnya yang terus komat-kamit bicara.
"Kalau kau berjalan lurus lagi, ke belakang Makam Pahlawan itu, kurang lebih 300 meter, di sana ada kampus besar. Pendirinya juga seorang pahlawan. Syeikh Zainudin Abdul Madjid, beliau adalah kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB yang sekarang. Di zaman pendudukan Jepang, beliau beberapa kali didatangi untuk negosiasi. Untuk diajak kerjasama oleh Jepang. Jepang takut dengan jamaah dan massa dari Beliau. Tapi Beliau dengan tegas menolak"
"Beliau masih hidup sekarang?"
"Sudah meninggal tahun 1997, dan sekarang hanya diurus oleh anak-anaknya"
Aku mengangguk kecil. Tode memandangku lembut sekali, entah kenapa badanku terasa panas dingin.
"Baiknya kita cari makan dulu" Tode menarik lenganku.
Dapat kurasakan aliran darahku bergerak lebih cepat dari biasanya. Tangan Tode terasa lembut. Dan aku mulai ragu dengan keyakinanku selama ini, bahwa semua lelaki identik dengan hal keras. Aku sering melihat Bapak dulu. Tubuhnya kasar, kulitnya keras. Dan tangannya sering menampar pipi mendiang Ibu. Apalagi kata-kata yang keluar dari mulutnya, jijik dan kasar. Sering menyebut nama binatang dari a sampai z. Tapi Tode tidak, dia tidak begitu. Aku semakin jatuh cinta padanya.
"Ini adalah warung orang Jawa. Sangat banyak orang Jawa merantau kesini dan membuat usaha mereka sendiri. Mereka banyak menjual tahu tek, gado-gado, cilok, atau nasi goreng. Rata-rata dari mereka terbilang sukses. Banyak yang bikin rumah sendiri. Meski banyak juga yang menikah lagi dan melupakan istri mereka di Jawa" Tode dengan lahap menyantap tahu tek yang sudah tersaji di depannya.
Aku menatapnya dengan teliti, caranya mengunyah, bibirnya yang merah, keringat di keningnya karena kepedesan. Dia begitu tampan. Menggemaskan.
"Nanti kita akan istirahat di Masjid Agung Selong. Di depan masjid itu, ada sebuah gedung kecil. Namanya Gedung Juang, nah di gedung itulah Tuan Guru Faisal meninggal saat penjajahan dulu. Sebenarnya Beliau bisa saja membunuh semua serdadu yang terlelap saat itu. Namun Beliau membangunkan mereka terlebih dahulu, dan Beliau yang lebih dulu ditembak oleh para serdadu. Sebab dalam Islam, tak boleh membunuh musuh yang sedang tidur. Mirip-mirip cerita Hamlet yang tak jadi membunuh pamannya yang sedang sembahyang" Tahu tek di depannya tinggal sedikit. Tode masih saja ngobrol sembari makan.
***
Tode. Apa kabarmu saat ini? Lelaki gondrong yang akhirnya berterus terang tentang asal-usulnya padaku.
"Jujur. Aku sebenarnya turunan Lalu. Keluargaku selalu bilang kalau kami adalah turunan bangsawan, turunan darah biru. Adikkku bernama Baiq Eliana Mahisa. Dia dilamar oleh pemuda biasa dari Ampenan. Kedua orang tuaku meminta lamaran yang terbilang wah pada pemuda itu. Mereka meminta uang 200 juta. Sedang keluarga pemuda itu tak punya apa-apa. Hingga lamaran itu tak pernah menemui sepakat. Orang tuaku selalu bilang, keluarga kami tak pantas menikah dengan pemuda biasa. Padahal adikku amat mencintai pemuda itu. Lantas adikku dijodohkan dengan pemuda lain yang mereka anggap dari keturunan bangsawan juga. Lambat laun, pernikahan itu membuat adikku depresi dan akhirnya gila. Sampai saat ini masih dirawat di Selagalas. Aku coba berontak dengan semua itu, aku kabur dan meninggalkan nama depan yang diberikan mereka"
Ada raut sedih diwajahnya saat itu. Ia seperti ingin menangis, namun sekuat tenaga Ia menahannya. Mungkin perasaan sedihnya saat itu hampir sama atau mungkin saja lebih besar dari apa yang kualami sekarang.
Di ruangan ini, aku masih terdiam, masih mengingat Tode. Sampai pada seorang mengetuk pintu kamar dan berucap, "Pengantin perempuan sudah siap Mas. Mas sebaiknya keluar. Acara segera dimulai" Dadaku bergetar hebat mendengar ucapan itu.
Aku tak yakin, apakah perempuan yang sudah mengenakan baju Kebaya di luar itu mampu menutup lubang besar yang telah dibuat Tode di dadaku.
Aku kemudian berjalan pelan keluar kamar, menuju halaman depan rumah. Aku melihat para tamu sudah banyak berdatangan, termasuk Bapak penghulu. Dan pengantin perempuan itu terlihat cantik, Ia tersenyum menatapku yang datang menghampirinya.
"Apakah pengantin laki-laki sudah siap?" Bapak Penghulu bertanya padaku. Tatapannya begitu tajam.
Aku termenung. Entah mengapa di saat-saat seperti itu, aku teringat apa yang diucapkan mendiang Ibu sebelum beliau meninggal.
"Nak, jika nanti kau menikah. Menikahlah dengan seorang yang bisa membahagiakanmu. Seseorang yang apabila kau melihatnya saja, seluruh tubuhmu bergetar. Dan hatimu bahagia tak terkira. Sebab pernikahan hanya sekali, dan kau musti bahagia" Aku ingin menangis mengingat ucapan Ibu. Aku masih terdiam dan belum menjawab yang ditanyskan Bapak Penghulu. (***)
Biodata Penulis: Rifat Khan, tinggal di Lombok Timur, bergiat di komunitas Rabu Langit, lembaga yang fokus memasyarakatkan dunia sastra di daerah ini.