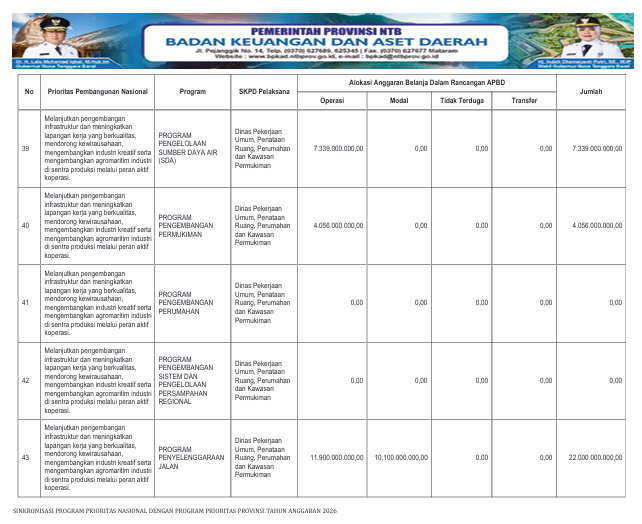Cerpen : Ani DS.
Aku memandangi perempuan di hadapanku. Wajahnya kuyu, dengan kulit kusam tak terurus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang sama sekali tak bersinar. Dia menarik bibirnya ke atas, mencoba tersenyum. Wajahnya sedikit berubah manis, tapi pancaran matanya tetap sama. Tidak ada senyum di situ. Lalu senyum di bibir itu menjejak di bawah tulang pipi, antara mulut dan hidung.
Usianya belum 40, tapi keletihan yang bertarung dengan musim dan cuaca, juga gaya tarik bumi tampak nyata di raut itu. Paras itu tidak menunjukkan kerja keras yang berbuah bahagia seperti selalu ia katakan. Tidak ada remah bahagia itu meski hanya sekadar di ujung bibir atau mata. Ia buram.
Perempuan itu menyibak rambutnya dengan sisir. Tampaklah helai-helai kelabu. Tidak terlalu jelas, tidak cukup banyak, tidak cukup membuat wajahnya berubah semakin dramatis. Hanya melengkapi segala ketidakbenaran pembelaannya terhadap kesempurnaan dan bahagia yang ingin ia tunjukkan.
Ia tidak lagi muda. Ia tidak berbahagia.
Aku masih memandanginya. Ia balik menatapku dengan mata layu itu. Mungkin karena ini sudah malam dan ia seharian tadi tak pernah berhenti bekerja, berpikir, merenung.
Tapi tidak. Itu bukan wajah letih karena kerja semata. Wajahnya mengingatkanku pada seorang aktivis perempuan yang kuwawancarai pagi tadi. Mereka tidak mirip. Sama sekali tidak. Aktivis tadi itu memiliki kulit mengkilap bak patung porcelain. Putih merah jambu dan mengkilap sehat. Muda dan bernutrisi.
Usia mereka mungkin tidaklah jauh. Maksudku si aktivis justru berada pada penghujung kepala empat, namun tampil seolah masih di awal 30. Mungkin benar kematangan dan usia puncak itu ada di kepala empat. Bisa jadi. Tapi perempuan ini masih di awal 30 namun terlihat sudah menyentuh 40. Terlalu jauh.
Tidak saja wajah. Perempuan di hadapanku ini juga mengingatkanku pada cerita si aktivis itu betapa perempuan di daerahku tercinta ini lahir seolah jauh dari peradaban. Tidak terbelakang secara fisik semata, mereka juga menghadapi dinding tebal pola pikir primordial, patrilineal, dan sederet ungkapan lain yang tentu saja tidak mereka kenal.
Perempuan itu menyimpan jiwa yang sakit halnya banyak perempuan yang diceritakan aktivis itu. Jiwa yang terkungkung terbelenggu pada kepongahan berlatar penyerahan diri bodoh. Sebutlah apa saja: penyerahan diri, pengabdian, keikhlasan. Mengalah demi semua. Hanya mengharap surga. Tak tahulah itu sebenarnya apa.
“Kau sakit,” bisikku pada perempuan itu.
Ia tidak bereaksi membalasku. Hanya matanya menantang menyangkalku. Mata letih berlingkar hitam yang memaksa menerobos mataku. Tajam dan pahit.
“Kau butuh istirahat, tidurlah.”
Mata itu menantangku sekali lagi, seolah berkata sudah banyak waktu yang dihabiskannya untuk terpejam. Terpejam yang tidak membuatnya lebih segar. Terpejam yang tidak membuat lingkaran hitam itu pergi.
“Selamat malam, ma,”
Dua anakku tiba-tiba sudah berdiri mengapitku. Yang sulung di kiri, si bungsu di kanan. Mereka memberikan ucapan selamat malam sambil mencium pipiku. Seperti biasa. Ciuman itu kubalas ciuman dan pelukan panjang. Ritual malam yang kubiasakan selain menggosok gigi, juga berdoa. Pelukan baik untuk kesehatan jiwa. Anak-anak butuh tumbuh sehat jiwa dan raga.
Perempuan itu kembali memberikan tatapan tajam penolakannya padaku ketika anak-anakku telah berlalu. Penolakan pedas menurutku. Ia tidak tahu apa-apa tentangku.
Kami tak terlalu sering bertemu bercerita. Kami tak terlalu sering saling membaca. Namun semakin sering aku melihat menatapnya semakin yakin aku akan sengkarut di hidupnya, ketidakbahagiaannya.Tapi lebih sering ia berbalik menuduh justru akulah yang begitu.
“Tidurlah,” kuingatkan ia sekali lagi, “masih banyak kerja esok.”
Ia membalasku tak peduli. Alih-alih berangkat tidur, ia sibuk mengoleskan sebentuk krim pada mata berlingkar hitam itu. Sebuah krim buatan produsen kosmetik luar negeri yang konon tidak dicobakan pada tikus atau hewan laboratorium lainnya. Produsen yang peduli lingkungan, juga peduli pada perempuan. Begitulah mereka menjual dirinya. Kepedulian pada perempuan dan lingkungan ini adalah kampanye seksi yang sangat menjual. Terutama bagi perempuan di dunia ketiga, dunia yang baru melek pada segala hal olahan barat. Tak heran gerainya bertaburan di banyak kota.
Selesai dengan krim mata yang berakhir pijatan lembut itu, ritual barunya berlanjut. Ada krim lain yang disapu lantas ditepuk-tepukan ringan di seluruh wajahnya. Krim anti penuaan dini, begitu yang tertulis.
Aku mengamatinya. Wajahnya terlihat sedikit berkilau lembut. Tapi tidak ada yang berubah di mata itu. Letih dan risaunya tak luntur.
Seolah sadar, dicampakkannya krim-krim itu ke tempat sampah yang ada di sudut kamar.
“krim itu tidak salah,” aku terperangah.
Ia menatap antara benci dan kecewa. Rasa itu ditambah lingkaran hitam di bawah mata mengubahnya menjadi hantu yang suka menakuti orang di film horor Indonesia. Hantu patah hati yang marah karena cemburu. Amarah yang membakar hingga ke jantungnya.
Amarah yang membuatnya tersungkur menjelma mahluk antara bumi dan langit. Amarah yang membuatku tercengang lalu tak berbuat berkata apa jua.
Amarah, pada kulminasinya akhirnya menundukkannya menjadi manusia paling lemah. Mengembalikannya pada wujud perempuan bermata letih berlingkaran hitam di sekelilingnya. Perempuan yang akhirnya mengalah pada air mata. Ia menangis. Tangis dan air mata adalah benteng terakhir segala rasa, memagari kekuatan sekaligus kelembutan jiwa. Ia memilih itu menjadi penjaganya.
Aku mematung meresapi amarah dan kesakitannya. Apa yang dirasanya ikut menjalar menggerayangiku. Sesak menusuk menghujam. Nyeri menggigil aku.
Lalu ada tangan-tangan mengelus leherku. Sudah itu sentuhan bibir berkali-kali, lalu sebuah bisikan menyapa telingaku…
Aku bergidik. Terlonjak dari dudukku, kudapati suamiku, setengah memelas mengharapkanku. Aku menggeleng ketakutan. Suamiku melihatku dengan luka, kecewa, berbaur kekhawatiran. Aku mengerang. Ia menunduk tak rela melihatku. Maka ia berlalu, mengalah.
Aku kembali duduk, menghadapi wajah itu, perempuan dengan lingkaran hitam di matanya. Mata itu tertawa menang sekali ini. Larut sudah segala yang kusaksikan sebelumnya. Sedih luka kecewa amarah itu raib.
“Sudah kukatakan kau yang sakit,” ejeknya.
Aku meringis, tapi, “aku baik-baik saja.”
Tak peduli, ia tertawa keras. Tawanya seolah menembus gendang telingaku. Memantul dari langit-langit lalu menyerbu dari empat penjuru mata angin dan masuk meliuk sekaligus ke dalam labirin di telingaku. Itu lebih sakit dari tangis yang menelusup di hatiku karena amarahnya.
“Siapa yang mau kau bodohi?”
Kenapa aku harus membodohi siapa? Tugasku membuat segala makna terang benderang. Lugas. Tidak membelit, tidak meriap-riap. Tidak menghakimi, tidak membodohi.
Siapa yang akan kuperbodoh? sudah cukup bodoh tanpa perlu dibodohi. Dia main-main.
Dia tertawa sekali lagi. Lebih tajam membahana.
Aku sungguh tidak suka. Aku berdiri, meninggalkannya. Kupindahkan saklar ke posisi off. Remang. Ia memudar. Tawanya masih bergema di telingaku.
Malam sudah jauh, aku harus tidur, besok masih hari kerja. Banyak naskah yang harus kuselesaikan.
Kurapikan tempat tidur dan berbaring. Tidur seorang diri seperti setahun terakhir. Tawa perempuan itu masih terdengar mengejek melecehkan. Dan aku terperangkap terkungkung olehnya.
Aku sungguh letih, butuh beristirahat dari semua apapun. Aku tidak sudi terperangkap begini. Kumatikan lampu tidur di sisi pembaringan. Gelap sudah. Kini giliran ia, perempuan itu, terperangkap bersama tawa kejamnya, di dalam cermin.***