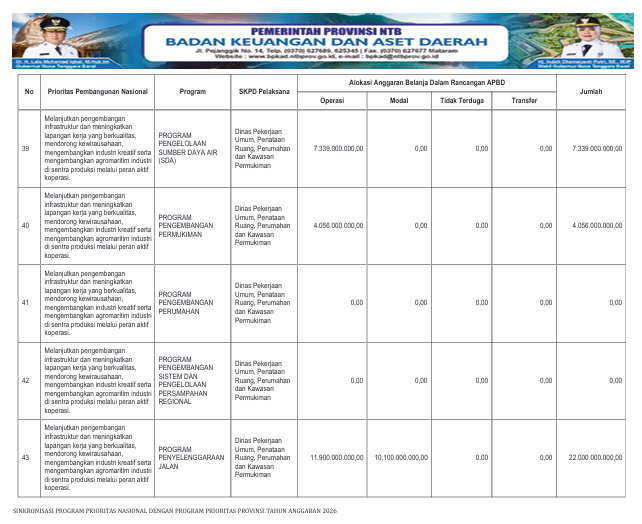Desember, penghujung tahun masehi telah tiba. Bulan ini banyak peristiwa penting yang bisa diingat. Mulai dari Hari Aids sedunia, Hari Artileri, Hari Hak Asasi Manusia, sampai Hari Ibu. Yang terakhir ini tentu yang paling akrab karena sangat dekat dengan semua orang. Hari Ibu akan tiba 22 Desember. Hari ini biasanya untuk banyak-banyak mengingat kebahagiaan yang ditebar seorang Ibu. Siapa yang tak lahir dari seorang ibu?
Hari Ibu ditetapkan melalui Dekret Presiden no. 316 tahun 1953, pada pembukaan peringatan kongres perempuan Indonesia ke 25. Kongres perempuan yang ditujukan meningkatkan hak-hak perempuan, utamanya dalam pendidikan dan pernikahan. Keseteraan jender, begitu sebutannya.
Tapi perayaan hari ibu kini lebih identik penghormatan dan berbagi kebersamaan dengan ibu atas perannya sebagai ibu, sebagai perempuan yang menyumbang hidup bagi generasi berikutnya, bukan sebagai perempuan yang memiliki hak (dan kewajiban) sama dengan jender lainnya. Sedikit bergeser dari latar belakangnya.
Tak apa, tidak terlalu buruk, sebab negara ini masih memiliki 21 April, Hari Kartini, sebagai penanda perjuangan perempuan meraih hak yang dipasung kekuasaan atas nama budaya patriarki. Membuktikan diri, perempuan Indonesia masih harus berjuang keras untuk itu. Walaupun pada praktiknya kaum perempuan Indonesia sebelum Kartini, sebelum ribut-ribut soal emansipasi sudah banyak yang menunjukkan kemampuan dan kebisaan mereka setara dengan laki-laki.
Kembali ke tujuan kongres perempuan. Kita perlu menggarisbawahi pada meningkatkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan perkawinan. Lebih tebal lagi pada hak. Boleh dicetak miring pula.
Hak dalam pendidikan mungkin sudah bisa dinikmati banyak perempuan, meskipun bila masuk lebih jauh ke daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) banyak pula yang masih harus berjuang lebih keras, tapi dalam perkawinan, sangat sedikit perempuan yang sudah memiliki dan menyadari haknya, apalagi mendapatkannya.
“Perempuan itu harus mandiri,” kalimat penyemangat ini disampaikan seorang perempuan berpendidikan, cerdas, dan aktif. Sebuah optimisme, ketegaran dan keberanian. Tapi bila dicermati itu adalah bentuk keputusasaan terhadap perilaku masyarakat kita, terhadap anggapan atas kemampuan perempuan.
Mandiri. Tidak bergantung pada orang lain. Menggali makna itu perempuan diharapkan bisa melakukan segalanya sendiri. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, yang 'diberi' ruang mengoptimalkan potensinya, harus menyiapkan tenaga dan pikiran ekstra. Bekerja di luar rumah, pulang mengurus rumah. Berpikir keras ketika di luar rumah, ketika pulang harus berpikir tentang dan untuk rumah.
Perempuan yang bekerja di luar rumah ini dituntut seperti Wonder Woman bahkan seperti hujan bulan Juni, yang lebih tabah, lebih arif, lebih bijak, lebih sabar.
Di luar rumah, dalam dunia kerja perempuan boleh memiliki hak dan kedudukan sama dengan laki-laki, tapi begitu sampai di rumah, urusan domestik tetap menjadi jatah perempuan. Tak usah terlalu muluk berpikir tentang laki-laki mencuci piring, mencuci baju, atau menyeterika, mengurus anak yang bukan ranah domestik saja boleh disurvey berapa banyak laki-laki yang sadar bahwa itu bukan hanya urusan perempuan?
Benarlah bahwa madrasah pertama seorang anak adalah Ibunya, bahkan kecerdasan juga diwariskan dari ibu, tapi menurut salah satu tokoh yang banyak berfokus pada perkembangan anak dengan pendekatan Psikososial, Erik Erikson, seorang tokoh New Freudian Psikoanalitik menyebut pada usia 2 – 3 tahun ayah adalah orang paling signifikan. Pada fase ini anak belajar untuk mandiri, dimulai dengan usahanya untuk berdiri dengan kakinya, berjalan dan mengeksplorasi dunia sekitarnya. Kegagalan untuk berdiri dan berjalan akan membuat keyakinan diri yang salah bahwa ia tidak mampu mandiri. Apa jadinya tanpa sosok tangguh seorang ayah di sisinya, yang membentuk kepercayaan dirinya?
Selaras dengan itu, Dr. Anna Sarkadi, dari Departement of Women's and Children's Health di Uppsala University, Swedia, dalam ScienceDaily mengungkapkan bahwa anak-anak akan mendapatkan manfaat positif jika memiliki keterlibatan aktif dan teratur dengan Ayah. Hal itu didasarkan kajian terperinci dalam kurun cukup panjang, 20 tahun.
Banyak dampak negatif ketidakhadiran Ayah ini. Kita bisa menemukannya dengan mudah di buku parenting populer. Dampak terbesar bisa dialami anak perempuan. Salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada pernikahan usia anak.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2015 angka perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun) mencapai 23 persen. Trennya menunjukkan penurunan tapi tidak menggembirakan. Tujuh persen dalam tujuh tahun. Dan prevalensinya lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan. 27,11 persen berbanding 17,09 persen.
Kita boleh berdebat bahwa itu bukan penyebab utama, ada semacam lingkaran "setan" yang bekerja, tapi kita tentu sepakat bahwa itu adalah satu dari sekian faktor masih tingginya angka perkawinan anak, bahkan di NTB yang Gubernurnya telah mengeluarkan Surat Edaran (no.150/1138/Kim tentang Pendewasan Usia Perkawinan) guna menekan angka perkawinan usia anak ini.
Selain itu fenomena Father’s Hungers, munculnya yatim-yatim psikologis adalah buah dari kesetaraan yang tidak setara dalam rumah tangga masyarakat kita. Ayah yang menyerahkan tumbuh kembang anak hanya pada ibu. Tidak percaya? Siapa yang hadir ketika pengambilan raport? Atau rapat wali murid? Atau mengantar dan menjemput anak, bahkan ketika ibu juga bekerja di luar rumah? Apalagi ketika seminar parenting? Mungkin hanya duapuluh persen yang hadir adalah kaum Ayah, laki-laki, sisanya adalah perempuan, ibu.
Negara sesungguhnya telah menyadari pentingnya posisi laki-laki, ayah, dalam keluarga. Karenanya sejak 2006 lalu Indonesia juga memperingati Hari Ayah. Cukup jauh dibanding negara-negara Eropa yang telah memperingati Hari Ayah sejak awal abad ke 12. Well, better late than never. Hari Ayah di Indonesia dideklarasikan pertama kali di Solo, Jawa Tengah, dan diperingati setiap 12 November. Sayangnya seperti halnya Hari Ibu, Hari Ayah pun tinggal sebagai peringatan semata. Sadar atau tidak kaum Ayah di negeri ini umumnya adalah laki-laki tradisional, dengan penekanan pada budaya patriarki, bukan family-man, laki-laki yang berorientasi pada keluarga. Pameo langkah laki-laki harus panjang dipahami sebagai laki-laki tempatnya adalah lebih banyak di luar rumah. Padahal ketika laki-laki menerima hak perempuan untuk bekerja di luar rumah semestinya ia menerima pula tanggung jawab, kewajiban untuk menyeimbangkan hak tersebut.
Dan berbicara hak perempuan dalam pernikahan, saya teringat ucapan tokoh yang diperankan Meryl Streep dalam sebuah film berjudul One True Thing. Film lain yang membawa Streep dinominasikan sebagai Artis terbaik katagori drama. Kalimat yang intinya setelah menghabiskan ribuan hari bersama dalam sebuah pernikahan kau akan menolerir banyak hal yang di usia muda tidak akan kau tolerir. Begitulah sungguh yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Tapi siapa yang menolerir? Percayalah, itu dilakukan lebih banyak oleh perempuan. Teman saya yang menyemangati untuk mandiri tadi mengakuinya. Dan dia tidak sendiri, “demi anak,” Itulah ungkapan lazim para perempuan ketika harus bertahan (walau tidak memungkiri anak-anak menjadi senjata laki-laki juga).
Persoalan kesetaraan ini memang butuh diurai lebih jernih ujung pangkalnya sehingga kita tidak gagap dan latah memaknainya. Perempuan tidak gagap, laki-laki tidak gagap, masyarakat kita menerima dengan baik. Akan tetapi kita tentu menyepakati bahwa setara adalah dalam hak dan kewajiban. Setara bukan persoalan anugerah, tidak berada pada lokus yang sama dengan konsekuensi lahiriah. Bahwa perempuan dianugerahi rahim untuk menyimpan benih dan mendukung perkembangannya hingga sembilan bulan, dianugerahi payudara untuk menyusui hingga genap dua tahun, sementara tangan dan kaki, anggota tubuh lainnya sama dianugerahi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Bukankah itu semestinya bermakna bahwa tugas lainnya sebagai khalifah di muka bumi adalah sama dan setara?
Lalu sebagai ummat muslim dengan Rasulullah sebagai role model, mengapa tidak mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah dalam rumah tangganya? Bukankah laki-laki selalu senang menggunakan sunah Rasul untuk menegaskan posisinya? Sunah Rasul jangan dipilih-pilih, dong. Bolehkah kita bersepakat? (***)
Penulis: ANI DS, Ibu rumah tangga di Lombok Timur