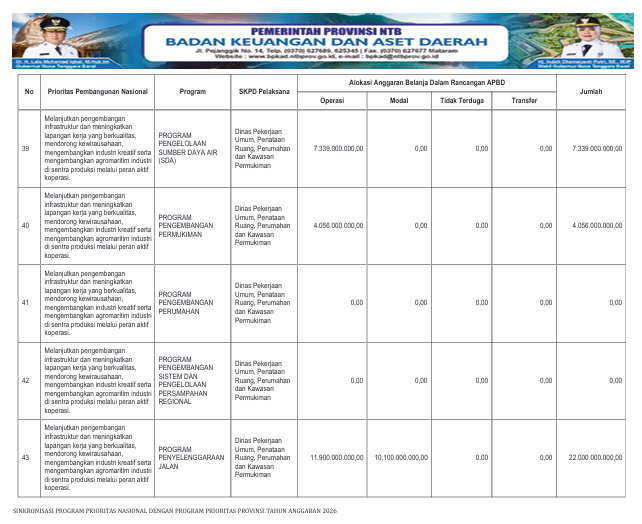“ Apa kabar Anda, dimana lebaran?” kata pak Ali saat melihat saya menghampiri sambil tersenyum dengan khas-nya.
“Baik Pak, di rumah Pak (stay at home), Bapak sehat ?” balik saya bertanya.
“ Sehaaat,” jawabnya.
Sore itu, sehari setelah lebaran saya berkunjung dan melihat pak Ali tidak berbeda, sama saja dengan style topi dan kostum olahraga, kacamata tanpa HP dan arloji hanya ditambah masker aja, waspada corona. Sederhana dan simple. Sore itu saya nikmati poteng dan jaje tujak ( jajan sasak) khas lebaran sambil bercerita banyak hal.
“Lebaran itu sama saja ya, dari kita kecil sama, saling memaafkan, merayakan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh dalam ramadhan, buka soal baju baru dan lainnya yaa,” terang pak Ali.
Oya, nama lengkapnya Mohammad Ali Bin Dachlan. Lahir di kampung pinggir perkotaan tepatnya Dasan Geres (sekarang kelurahan Geres), kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dasan Geres adalah kampung centra penghasil batu apung, banyak ladang tadah hujan, sedikit berdebu dan masyarakat hidup dengan nilai religius.
Gelisah akan keadaan, tapi sosok yang tidak letih apalagi lelah dan menyerah, tidak ada itu. Ali Dachlan, dulu remaja yang siap bertarung dengan kerasnya keadaan berjalan dalam terik panasnya matahari.
Peluh, keterbatasan membuatnya semakin bekerja keras dan tumbuh besar. Ali Dachlan akan tersenyum dan semakin kuat, erat memikul beban di pundaknya. Ia kekar, melangkah dan terus melangkah mengayuh harapan lurus ke-depan.
Ali Dachlan, memiliki mimpi dan harapan yang membedakan dengan kawan seusia-nya di kampung.
Sebenarnya, Ali tidak terlalu gemar berbicara, bukan pula sangat irit, hanya saja berbicara seperlunya dan membangun kultur diskusi sebagai sebuah tradisi dan layak untuk digemari.
------------
Sinar senja terlihat di celah gubuk Ali Dachlan. Ayam jantan mulai berkokok. Di kampung, pantang bahkan tidak boleh bermain saat senja tiba (pemalik) kata orang tua. Hewan ternak digiring gembala pulang ke kandang, satu persatu memasuki kandang dengan rapi.
Sementara itu kaki telanjang anak-anak kampung (dasan geres) berlari untuk mengaji. Tak peduli tanah berdebu sepanjang jalan, ingin cepat menuju langgar dan musalla.
Tidak terlalu lama senja itu, dan akhirnya warna keemasan hilang ditelan bumi. Malam pun tiba. Malam yang gelap hanya lampu tempel kecil cahaya pelita dengan asang tipis, hitam mengepul bertengker di tiang-tiang rumah penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rumah Ali.
Lampu tempel itulah sinar yang dibutuhkan untuk membantunya menyusun cerita yang akan dijalani. Cerita hidup di negeri yang belum benderang.
Ali Dachlan ingin membuatnya menjadi cerita yang lengkap tidak terpotong-potong. Di dalamnya, tertulis awan menggumpal yang gelap dan pekat. Awan tebal saling lipat dan ditutupi satu dengan lainya. Tidak ada sinar yang menunjukkan peta harapan. Atau mungkin tidak ada harapan waktu itu. Semua penghuni tidak ingin berharap karena buang waktu untuk berharap atau lelah seharian bekerja di tanah yang keras dan cadas dengan tenggorokan yang haus pula. Lalu untuk apa berpikir yang lain ? Ya, mereka benar tapi tidak bagi Ali Dachlan.
Menatap bintang yang bertabur indah di langit. Ingin melihat bulan walau tidak sempurna berpadu dengan bintang. Di atas ada langit yang luas bahkan jka bisa ingin melihat sampai lapis langit ke-tujuh.
Tidak semua warga di kampung itu ingin berpikir yang lain, buat apa mau melihat bintang dan bulan. Liat saja awan begitu tebal menyelimuti. Bukankah besok pagi harus berpikir kemana mau bekerja mencari uang untuk makan sehari-hari. Buat apa berpikir. Sudah gelap dengan awan tebal. Beras, umbi-umbian masih menjadi hal penting yang terpikir terus menghampiri .
Sebenaranya semua orang di kampung, desa terlebih lagi kota menginginkan hidup lebih baik. Pasti itu manusiawi. Semua ingin maju dan lebih maju selangkah dari orang yang mau maju lainnya. Manusiawi juga, jika tidak semua orang suka akan tantangan bahkan tidak ingin berharap atau memikirkan masa depan.
"Ayo makan poteng Anda! " sesekali pak Ali alihkan topik sambil menikmati sore. Saya pun terus menambah poteng dan jaje tujak hingga tersisa dua potong.
Ali terus mengenang. Waktu berputar menjadi malam diawali pagi yang kosong, siang yang hampa, sore yang tidak menentu, lagi malam menambah gelap. Usai mengaji anak remaja meranjak tertidur. Hanya itu, tidak ada tontonan pasti waktu itu.
“Orang tua selalu mengatakan cepat tidur, besok harus membantu untuk bekerja. Butuh tenaga yang kuat untuk menggarap sawah yang kadang tidak berair," tuturnya.
Suasana kampung Dasan Geres kala itu, begitu hening. Jangkrik dan kodok terdengar saling sahutan membuat irama yang indah dengan tempo yang teratur. Dari bilik warga lainya terdengar pula ibu-ibu mendongengkan anaknya tentang “timun bongkok “ dongeng rakyat dan terus diulang hingga anak menjemput mimpi.
Esok harinya, cerita bapak ibu guru di sekolah, cerita yang heroik menuturkan tentang sejarah dalam merebut kemerdekan. Semua dengan kerja keras.
Ali Dachlan kecil hingga remaja memliki mimpi, harus maju walapun belum nemukan caranya. Hanya mampu melihat bintang dan bulan silih berganti mengambil jadwal dengan awan.
Bintang di langit bertaburan, penunjuk jalan bagi Ali kecil keluar dari kegelapan. Seperti gelapnya balai ubin bambu luar halaman rumah yang terasa mulai lapuk. Bambu yang dirajut di saat waktu senggang selepas pulang sekolah.
Tempat itulah permadani, tempat menatap bulan dan bintang dengan bebas. Tempat dimana dihabiskan impian dan rencana besarnya. Tempat untuk melukis di langit gambar cita-cita. Remaja yang tidak takut bermimpi besar.
Malam itu terlihat banyak bintang walau sedikit terhalang oleh daun pisang yang mulai mengering menjulur di atap rumah. Ali Dachlan baru sadar cukup lama menikmati bintang malam sendirian, lalu bergegas ke gubuk berharap bertemu cara dalam wujudkan impian.
Mentari Pagi
Suara adzan subuh membangunkan warga kampung. Terdengar jelas kendati tidak secanggih toa zaman sekarang. Sementara itu, sinar pagi indah menyapu halaman, embun bening yang menempel di daun talas bergoyang jatuh teratur membasahi rumput teki pinggir rumah. Pagi sangat indah, kendati ada awan mencoba menutupi tapi tidak begitu lama.
“ Saya ke sawah dulu,” sapa orang tua di kampung Dasan Geres berpamitan pada sanak keluarga. Guru Dachlan ayah kandung dari Ali seorang guru ngaji di kampung.
Sebagai orang tua selalu berpesan kepada anaknya, hidup harus sederhana namun jangan takut bermimpi dan berpikir besar.
Begitu cepat pagi itu, remaja SMA di kampung bergegas berangkat sekolah ke kota. Kampung di pingir kota, Ali Dachlan harus berjalan membelah sungai. Sepatu lusuh tambah berdebu terpaksa harus ditenteng. Mengenakan pakian rapi ke sekolah bukan lagi menjadi hal penting baginya. Hanya belajar dan ingin berkembang yang terbayang.(wedo)
Bersambung. . . .