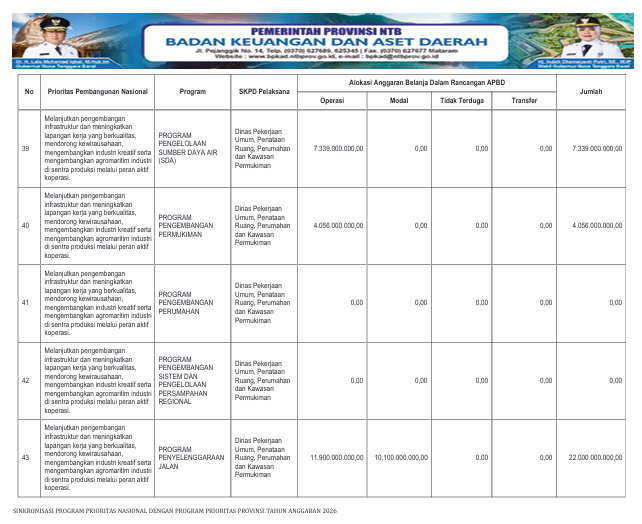Hanya berbekal sepotong harapan
secarik do’a dan mantra suci orangtua
aku berhasil “terdampar” di jawadwipa,
sebuah nagari asing pertama, yang kuinjak tanahnya.
Kampus adalah sudut pertama kota ini yang kujejali sehari-hari
konon, ini tempat dihuni gerombolan orang-orang ”pintar” cerdik cendikia, pandai bicara, juga fasih retorika.
Pada aroma kertas buku-buku
yang tertumpuk di sudut sempit kos-kosan
salik ilmu berlayar pada tiap lembarnya
menuju negeri negeri nun jauh
menziarahi dan bercakap imaginer dengan raksasa-raksasa pena dari berbagai belahan dunia.
Pada gedung-gedung kuno di kota ini
aku membaca jejak, cerita lampau.
tentang kehidupan dan perang
tentang cinta dan peradaban.
Pada lorong-lorong kota
aku mejumpai gerobak-gerobak kaki lima
berjejer mengais asa untuk hidup yang sementara
aku menyaksikan mata yang nanar
dan pijar-pijar harapan.
Pada bangunan gedung-gedung baru
aku menemukan para kuli
yang bermandikan peluh, dan berwajah lusuh
di balik punggungnya,
aku melihat bayang-bayang anak dan istrinya
yang rindu menanti kepulangannya.
Pada bahu-bahu jalan kota ini
aku menjumpai tukang becak
yang rata-rata paruh baya
aku melihat do’a di dada dada mereka.
Pada kelikir dan rel kereta
aku menemukan irama bising
membayangkan begitu banyak cerita
tentang gerak perpindahan anak manusia
untuk melayani kepentingannya
dari satu kota ke kota lainnya.
Pada malamnya, aku menjumpai warung-warung kopi yang selalu ramai sampai pagi
entah mereka berdiskusi, atau sekadar membuang sepi.
Pada pergaulan sosialnya,
aku menemukan banyak orang:
aneka etnis, ragam bahasa, agama, budaya dan asal negara.
Aku menyaksikan dadu-dadu kehidupan
keserakahan para pemodal
barisan para mantan yang remuk hatinya
orang orang yang gagal kuliah
desah tangis perempuan malam
anak kampung yang sok urban
dan segala jenis soal lainnya
dan pada pantai-pantainya, aku meninggalkan jejak
tentang cinta, luka, dan airmata
angin, ombak, pasir, dan pepohonan adalah saksi
mereka bicara tanpa aksara.
Kota ini benar-benar telah menempa
tentang arti hidup
dan segala hitam putihnya
Setelah semuanya, lalu apa?
rindu jalan pulang
rindu leluhur
rindu bapak
rindu kekasihnya bapak yang makin menua
rindu orang-orang yang harus kuhidupi hidupnya
rindu hening desa
rindu sungainya
rindu rumput rumput tua
Adakah yang lebih sakral, selain dari ingatan-ingatan?
Karya, Musa Mala
Yogya, 19 desember 2019